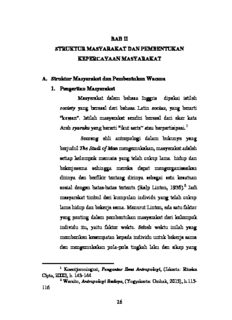Table Of ContentBAB II
STRUKTUR MASYARAKAT DAN PEMBENTUKAN
KEPERCAYAAN MASYARAKAT
A. Struktur Masyarakat dan Pembentukan Wacana
1. Pengertian Masyarakat
Masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah
society yang berasal dari bahasa Latin socius, yang berarti
“kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata
Arab syaraka yang berarti “ikut serta” atau berpartisipasi.1
Seorang ahli antropologi dalam bukunya yang
berjudul The Studi of Man mengemukakan, masyarakat adalah
setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan
bekerjasama sehingga mereka dapat mengorganisasikan
dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan
sosial dengan batas-batas tertentu (Ralp Linton, 1936).2 Jadi
masyarakat timbul dari kumpulan individu yang telah cukup
lama hidup dan bekerja sama. Menurut Linton, ada satu faktor
yang penting dalam pembentukan masyarakat dari kelompok
individu itu, yaitu faktor waktu. Sebab waktu inilah yang
memberikan kesempatan kepada individu untuk bekerja sama
dan mengemukakan pola-pola tingkah laku dan sikap yang
1 Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2000), h. 143-144
2 Warsito, Antropologi Budaya, (Yogyakarta: Ombak, 2015), h.115-
116
26
27
bersifat timbal balik, dan menemukan teknik-teknik hidup
bersama. Dalam sebuah masyarakat terdapat sosial control
yang berfungsi mengatur masyarakat dan sistem serta
prosedur yang mengatur kegiatan dan tindakan anggota
masyarakat. Seluruh sistem berfungsi sebagai pengawas
sosial. Pengawas sosial meliputi sistem ilmu pengetahuan,
ilmu teknik empiris yang digunakan oleh manusia untuk
mengelola lingkungannya, dan pengetahuan non empiris yang
mengatur sikap dan kelakuan magis atau keagamaan,
termasuk pula etika, sistem hukum, moralitas, ritual, dan
mitologi.3
Lama-kelamaan wadah yang disebut sebagai
masyarakat, dinamakan sistem sosial. Istilah masyarakat lebih
banyak dipergunakan sebagai sinonim dari negara atau bahkan
peradaban (civilization). Di dalam sejarah perkembangan
sosiologi sebagai sesuatu ilmu pengetahuan, para sosiolog
senantiasa berusaha untuk mengadakan klarifikasi terhadap
masyarakat-masyarakat yang ada. Para sosiolog pada abad ke-
19 mengadakan klarifikasi yang tajam antara masyarakat yang
sederhana dengan masyarakat modern yang kompleks. Dari
uraian tersebut Durkheim membedakan antara masyarakat
dengan struktur “ segmental “ dengan yang mempunyai
struktur “organic”. Yang pertama adalah masyarakat yang
terdiri dari bagian-bagian yang hampir-hampir merupakan
3 Beni Ahmad Sabeni, Pengantar Antropologi, (Bandung :
PUSTAKA SETIA, 2012), h. 137-140
28
replika dari masing-masing. Yang kedua merupakan
masyarakat yang mempunyai diferensiasi yang kompleks,
dimana terjadi hubungan organis antara bagian-bagian dari
masyarakat tersebut.4
Masyarakat menurut Durkheim adalah realitas sui-
generis- yakni masyarakat memiliki eksistensinya
sendiri.5Maurice Duverger juga memberikan pengertian
tentang masyarakat yaitu, masyarakat tidak dipandang sebagai
suatu kelompok individu atau sebagai penjumlahan dari
individu-individu semata-mata. Masyarakat merupakan suatu
pergaulan hidup, oleh karena manusia itu hidup bersama.
Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena
hubungan dari anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat
adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama
manusia yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan.6
Selain itu ada beberapa unsur yang bisa mengikat satu
kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat yaitu, pola
tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya
dalam batas kesatuan itu, adat- istiadat, norma-norma, hukum,
dan aturan-aturan yang khas meliputi sektor kehidupan serta
4 Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur
Masyarakat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983) , h.105-106
5 Pip Jones, alih bahasa oleh Achmad Fedyani Saefuddin, Pegantar
Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-
Modernisme,.(Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010 ) , h. 45
6 Solaeman B Taneko, Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar
Sosiologi Pembangunan,.(Jakarta : Raja Grafindo Persada, cetakan kedua
1993), h. 11
29
suatu kontinuitas dalam waktu, serta adanya suatu rasa
identitas di antara para warga atau anggotanya, bahwa mereka
memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari
kesatuan-kesatuan manusia lainnya. Dari uraian di atas maka
dapat ditarik suatu definisi masyarakat secara khusus :
masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi
menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat
kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.7
Biasa bagaimanapun juga penggunaan istilah
masyarakat tak akan mungkin dilepaskan dari nilai-nilai,
norm-norma, tradisi, kepentingan-kepentingan dan lain
sebagainya. Oleh karena itu, maka pengertian masyarakat tak
mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian.
Sebenarnya suatu masyarakat merupakan suatu bentuk
kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri pokok,
sebagai berikut:
a. Manusia yang hidup beragama secara teoritis, maka
jumlah manusia yang hidup berjumlah lebih dari dua
orang. Di dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi,
tidak ada suatu ukuran yang mutlak ataupun angka yang
pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang ada.
b. Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama.
c. Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan
bagian dari suatu kesatuan.
7 koentjoroningrat,op. cit., h. 145-147
30
d. Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi
patokan bagi perilaku yang dianggap pantas.
e. Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan
kebudayaan tersebut.8
2. Struktur Masyarakat
Struktur sebarang ihwal yang kita jadikan unit objek
(entity)- suatu atom, molekul, kristal, organisme, masyarakat-
mengacu pada hubungan antar bagian yang kurang-lebih
tetap bertahan, demikianlah istilah “struktur sosial”.9
Struktur Sosial atau yang biasa disebut dengan
struktur masyarakat, dalam antropologi konsep struktur sosial
berkembang dalam pendekatan struktur-fungsional dari
antropologi sosial di Inggris10. Struktur sosial merupakan
pedoman bagi tingkah laku manusia. Konsep struktur sosial
mengandung arti, di dalam konsepsi mengenai struktur sosial
terkandung relasi sosial yang berlaku sebagai kenyataan, atau
relasi sosial yang konkret, dan meliputi role expectations,
yaitu tingkah laku yang diharapkan secara timbal balik, ideal
patterns, yaitu yang sifatnya relatif konstan dan bersifat
menetap.11
8 Soerjono Soekanto,op. cit., h. 107
9 David Kaplan, Teori Budaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
h.139
10 Pip Jones, alih bahasa oleh Achmad Fedyani Saefuddin,op. cit.,
h.44
11 Beni Ahmad Sabeni, Pengantar Antropologi, (Bandung: Pustaka
Setia, 2012). h.142
31
Bagi Durkheim, pencapaian kehidupan sosial manusia
dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat, yang ia
sebut solidaritas sosial, di mantapkan oleh sosialisasi yang
melalui proses tersebut manusia secara kolektif belajar
standar-standar atau aturan-aturan perilaku. Istilah Durkheim
untuk hal ini adalah “fakta sosial”. Maka fakta sosial ini hanya
bisa dilihat melalui konformitas individu-individu kepadanya,
fakta sosial itu menurut Durkheim berada “eksternal” dan “
mengendalikan” individu-individu ini.12 Konsepsinya tentang
struktur sosial itulah yang mendorong Durkheim mendukung
penggunaan ilmu pengetahuan (sains) untuk menjelaskan
kehidupan sosial. Metode ilmiah yang dikembangkannya
dikenal sebagai positvisme. Prinsip pemandu bagi positivisme
adalah jika sesuatu terjadi dalam alam, ini disebabkan oleh
sesuatu yang lain dalam alam.
Bagi Durkheim, struktur sosial sama objektifnya
dengan alam itu sendiri. Menurutnya, sifat struktur diberikan
kepada warga masyarakat sejak mereka lahir, sama seperti
yang diberikan alam kepada fenomena alam, yang hidup
maupun tidak. Kita tidak memilih untuk meyakini sesuatu
yang kini kita yakini atau memilih tindakan yang kita ambil
sekarang. Kita belajar untuk berfikir atau melakukan semua
12 Pip Jones, alih bahasa oleh Achmad Fedyani Saefuddin, op. cit., h.
45
32
itu. Aturan-aturan kebudayaan yang sudah ada menentukan
gagasan dan perilaku kita melalui sosialisasi.13
Para antropolog Inggris kontemporer yang mengikuti
jalan fikiran Radcliffe-Brown menyatakan bahwa struktur
sosial tak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Menurutnya,
struktur sosial sebagai jaringan-jaringan yang kompleks dari
relasi yang sebenarnya terdapat pada masyarakat. Dia
digolongkan dalam kelompok sosial Prancis bersama Emile
Durkheim dan Levy-Bruhl. Redcliffe-Brown mengatakan
bahwa objek penelitian antropologi sosial adalah kebudayaan.
Struktur sosial dalam masyarakat berada di belakang aktivitas
individu di dalam masyarakat. Artinya, struktur sosial harus
diabstraksikan dengan cara induksi dari kenyataan-kenyataan
kehidupan kemasyarakatan yang konkret.14 Akan tetapi
struktur sosial tetap merupakan kerangka acuan yang utama
(apabila dibandingkan dengan kebudayaan). Baginya struktur
sosial merupakan kenyataan empiris yang ada pada suatu saat
tertentu. Konsep struktur sosial dipergunakan untuk
menggambarkan keteraturan sosial, untuk menunjuk pada
perilaku yang diulang-ulang dengan bentuk atau cara yang
sama.
Sebagaimana halnya dengan antropologi, maka di
dalam sosiologipun konsep tersebut merupakan inti
pendekatan struktural-fungsional. Struktur sosial diartikan
13 Ibid ,. h. 49
14 Beni Ahmad Sabeni, op. cit., h.142-143
33
sebagai hubungan timbal-balik antara posisi-posisi sosial dan
antara peranan-peranan. Interaksi dalam sistem sosial
dikonsepkan secara lebih terperinci dengan menjabarkan
manusia yang menempati posisi-posisi dan melaksanakan
peranannya. Dari uraian di atas dapat dita rik kesimpulan
bahwa struktur sosial merupakan jaringan daripada unsur-
unsur sosial yang pokok dalam masyarakat.15
3. Pembentukan Wacana
Secara etimologis kata “wacana” (discourse) berasal
dari bahasa Latin discursus („mengalir secara terpisah‟ yang
ditransfer maknanya menjadi „terlibat dalam sesuatu‟ atau
„memberi informasi tentangsesuatu‟). Dlam bahasa Latin abad
pertengahan kata discursus selain berarti percakapan,
perdebatan yang aktif, dan juga keaktifan berbicara, kata ini
juga berarti orbit dan lalu lintas. Vass (1992;9) menjelaskan
makna „wacana‟ berikut ini:
a. (secara umum): tuturan, percakapan, diskusi;
b. Penyajian diskursif sederet pemikiran dengan
mnggunakan serangkaian pernyataan;
c. Serangkaian pernyataan atau ujaran, sederet pernyataan;
d. Bentuk sebuah rangkaian pernyataan/ ungkapan; yang
dapat berupa (arkeologi): wacana ilmiah, puitis, religius;
e. Perilaku yang diatur kaidah yang menggiring ke arah
lahirnya serangkaian atau sistem pernyataan-pernyataan
15 Soerjono Soekanto,.op. cit, h. 109-113
34
yang saling terkait (=berbagai bentuk pengetahuan)
(kedokteran, psikologi, dan sebagainya) ( misalnya, dalam
karya Michael Faucault);
f. Bahasa sebagai sesuatu yang dipraktikkan ; bahasa tutur
g. Bahasa sebagai suatu totalitas; seluruh bidang linguistik;
h. Mndiskusikan dan mempertanyakan kriteria validitas
dengan tujuan menghasilkan konsensus di antara peserta
wacana.16
Dalam pengertiannya, wacana dapat dibagi menjadi
tiga yaitu, level konseptual teoritis, konteks penggunaan, dan
metode penjelasan. Berdasarkan konseptual teoritis, wacana
diartikan sebagai domain umum dari semua pernyataan, yakni
semua ujaran atau teks yang mempunyai makna dan
mempunyai efek dalam dunia nyata. Sementara dalam konteks
penggunaannya, wacana berarti sekumpulan pernyataan yang
dapat dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu.
Sedangkan dilihat dari metode penjelasannya, wacana
merupakan suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan
sejumlah pernyataan.17
Van Djik memandang wacana secara umumnya
sebagai teks dalam konteks dan sebagai bukti yang harus
diuraikan secara empiris. Ia menunjuk ke satu aspek yang
16 Stefan Titscher, Metode Analisis Teks dan Wacana, (Yogyakarta;
Pustaka Pelajar, 2009), h. 42-43
17 Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk nalisis
Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing, (Bandung: Remaja
Rosdakarya,2002). h. 9-11
35
sangat penting, yaitu bahwa wacana itu hendaknya dipahami
sebagai tindakan, sifatnya yang bisa berdiri sendiri dan
tindakan komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting.
Di sini wacana memandang bahwa bahasa yang
digunakan dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk „praktik
sosial‟. Dengan menggambarkan wacana sebagai praktik
sosial menyiratkan adanya hubungan dialektik antara sebuah
peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, intuisi, dan struktur
sosial tersebut. Dengan kata lain, wacana ditetapkan dan juga
dikondisikan secara sosial aspek-aspek sosial tersebut
meliputi situasi, objek pengetahuan, dan identitas sosial, serta
hubungan antara orang-orang dan berbagai kelompok orang.18
wacana, teks dan konteks
Sebetulnya, antara wacana, teks, dan konteks
merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Sebagaimana menurut Guy Cook misalnya, ada tiga hal yang
sentral dalam pengertian wacana: teks, konteks, dan wacana.
Ia mengartikan teks sebagai semua bentuk bahasa, bukan
hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga
semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar,
efek suara, cerita dan sebagainya. Konteks memasukkan
semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan
mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam
bahasa, situasi di mana teks tersebut diproduksi, fungsi yang
18 Gazali dkk, Metode Analisis Teks dan Wacana, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009). H.43-44
Description:143-144. 2 Warsito, Antropologi Budaya, (Yogyakarta: Ombak, 2015), h.115-. 116 struktur masyarakat, dalam antropologi konsep struktur sosial berkembang .. pawukon Jawa) berdampingan dengan kalender India. Tidak .. masyarakat telah mendorong lahirnya banyak kajian tentang agama.